Gus Baha' Sang Santri Lintas Zaman
ditulis oleh al-faqir Abdi Kurnia
Entah berapa banyak kalimat yang bisa dituliskan untuk memuji sosok Kiai Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha. Beliau hadir seperti "menantang" intelektualisme moderen yang mempersyaratkan gelar akademis di depan atau di belakang nama pribadi. Gus Baha' tampil dengan sebuah afirmasi bahwa intelektualisme tidak melulu hadir di ruang kelas atau forum seminar. Tapi, intelektualisme juga bisa hadir di majelis lekar, atau forum cangkrukan yang digelar dengan santai sambil ditemani kopi dan beberapa bungkus rokok.
Gus Baha' merupakan figur santri yang pernah dideskripsikan secara ideal oleh Kiai Ahmad Baso di berbagai tulisan. Bahwa intelektualitas dan intelektualisme dunia pesantren, sebagaimana ditegaskan Kiai Baso, bukan dengan mengikuti alur nalar berpikir Barat yang liberal.
Kiai Ahmad Baso, di dalam karyanya, " Agama NU untuk NKRI" dan " Islam Pasca Kolonial" selalu menegaskan bahwa liberalisme pemikiran bukanlah senyawa orisinil dunia pesantren. Pesantren mempunyai khasanah dan manhaj-nya sendiri untuk berbicara tentang peradaban.
Bagi pembaca yang belum melihat tayangan pengajian Gus Baha', narasi yang diverbalkan oleh Kiai Ahmad Baso itu seperti mengawang-awang. Barangkali simpulan yang muncul adalah bahwa Kiai Ahmad Baso hanya mampu menyajikan contoh lama yang tidak kontekstual dengan kekinian. Namun, bagi yang pernah atau sering mengikuti kajian Gus Baha', maka narasi Kiai Ahmad Baso tersebut memang benar adanya.
Fenomena ketertarikan terhadap kajian Gus Baha' ini ternyata tidak saja terjadi di kalangan Warga Nahdliyyin. Dan sebenarnya ini tidak mengherankan. Kehadiran Gus Baha', seperti menjawab warga NU yang tengah dilanda kegalauan akibat meninggalnya para ulama sepuh. Setelah wafatnya Kiai Sahal Mahfuzh, Kiai Abdul Muchith Muzadi, Kiai Abdullah Faqih, dan Kiai Maimun Zubair, warga Nahdliyyin seperti kehilangan suluh. Para kiai muda, yang kini menjadi pemimpin pesantren belum dipandang "mampu" menggantikan para kiai kharismatik yang telah berpulang setelah menunaikan tugasnya.
Ketertarikan terhadap kajian-kajian Gus Baha' ternyata juga terjadi di kalangan non-Nahdliyyin. Adalah pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menyebut Gus Baha' sebagai manusia Qur'an di Indonesia pada masa sekarang ini. Pernyataan itu sesungguhnya mewakili opini yang berkembang di sekeliling ustadz yang mempunyai pengaruh besar di kalangan perkotaan.
Ketertarikan warga bukan Nahdliyyin terhadap Gus Baha' didasarkan kepada metodologi yang digunakan oleh Gus Baha' di dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang tidak melepaskan diri dari paradigma fikih yang dikuasainya. Bagi mereka yang tidak akrab dengan tradisi keilmuan NU, cara penyajian Gus Baha' tersebut terbilang langka. Karena selama ini, mereka hanya menerima penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat letterlijk dan bahkan terkadang disisipi oleh lathaif siyāsah (motif-motif politik yang tersembunyi).
Gus Baha', melalui topik-topik yang diangkatnya, seperti telah membaca apa yang sebenarnya dibutuhkan publik di luar pesantren. Beliau seperti tidak ingin memaksakan cara pandangnya di dalam memahami masalah kepada audiens yang mendengarkan. Itu bisa dicermati dari bagaimana beliau mencoba menyederhanakan deskripsi fikih yang rumit, ke dalam bahasa yang mudah, melalui perumpamaan yang mudah dimengerti siapa saja. Ketidakinginan Gus Baha' memaksakan cara pandangnya kepada audiens seringkali diartikulasikan dalam ungkapan yang jujur, " ini penting saya utarakan". Dari ungkapan itu, ada kesan bahwa audiens dipersilakan menilai sendiri pendapat yang disampaikan oleh Gus Baha'.
Masih banyak yang ingin dituliskan di sini tentang Gus Baha', namun karena keterbatasan ruang saya tidak bisa melanjutkan keinginan itu. Intinya, Gus Baha' adalah santri yang mampu melintasi semua zaman. Dan memang seharusnya santri NU seperti itu. Apalagi, dengan keberadaan UU Pesantren, tidak ada alasan lagi bagi santri untuk tidak mampu berbicara sesuai dengan konteks zamannya.
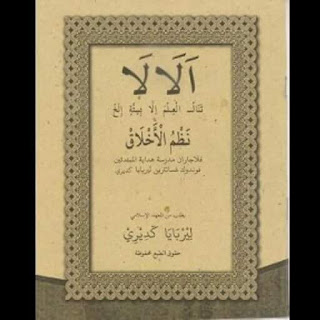

Komentar
Posting Komentar